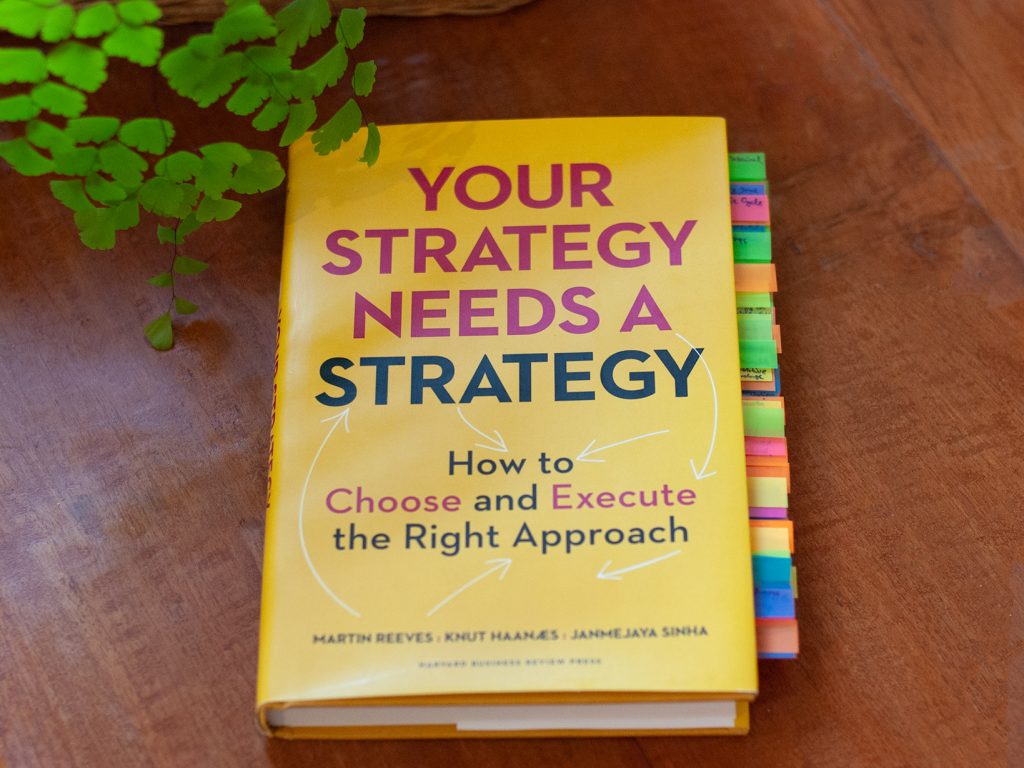
Your strategy needs a strategy melihat dunia melalui rear-view mirror, melihat ke belakang ketimbang ke depan. Melihat dunia sebagaimana adanya. Enggan melihat dunia dengan lebih kritis. Akibatnya, membaca buku ini seperti membaca sebuah executive summary sepanjang 200 halaman. Sebuah executive summary yang, at its best, terlalu menyederhanakan dunia, dan, at its worst, mendistorsi realita.
Di satu sisi, buku ini memberikan kontribusi baru mengenai jenis-jenis tantangan yang dihadapi oleh sebuah bisnis dan cara-cara yang tepat untuk menyikapinya, tapi di sisi lain, kesimpulan dan implementasinya disajikan dengan riset dan contoh yang agak ngambang, dengan analisa yang rasanya kurang “masuk”.
Ditulis oleh Martin Reeves, Knut Haanæs dan Janmejaya Sinha dari Boston Consulting Group, Your Strategy Needs a Strategy membahas mengenai berbagai jenis strategi yang tepat digunakan untuk menghadapi tantangan market dan bisnis yang berbeda-beda.
Karakter pasar dan tren bisnis, menurut mereka, bisa dibagi menjadi tiga buah tantangan:
a. Tantangan menurut tingkat Malleability (Seberapa gampang market/industrynya bisa dibentuk)
b. Tantangan menurut tingkat Unpredictability (Seberapa predictable market dan industrynya)
c. Tantangan menurut tingkat Harshness (Seberapa keras dan profitable market/industrynya.)
Dengan tiga dimensi tantangan tersebut, perusahaan mempunyai lima jenis strategi yang bisa diterapkan:
1. Classical Strategy ketika arah industri dan market bisa ditebak tapi sulit dibentuk,
2. Visionary Strategy ketika arah industri dan market bisa ditebak dan bisa dibentuk,
3. Adaptive Strategy ketika arah industri dan market susah ditebak dan sulit dibentuk,
4. Shaping Strategy, ketika arah industri dan market susah ditebak tapi bisa dibentuk,
5. Renewal Strategy, ketika market sedang keras yang ditandai oleh growth yg rendah, sehingga perusahaan membutuhkan pembaharuan bisnis, berupa pembaharuan internal maupun pemilihan market yang lebih sustainable.
Dan dalam usahanya, mereka sanggup memberikan kacamata baru untuk melihat tantangan market yang dihadapi sebuah bisnis pada umumnya. Sayangnya, buku ini mulai bermasalah ketika kita memasuki detil implementasi dan justifikasi frameworknya.
Your Strategy Needs a Strategy sekedar melihat business & management practice apa yang dilakukan mayoritas perusahaan dan membaginya menjadi kuadran-kuadran strategi tanpa melihat prakteknya dengan lebih kritis. Tidak ada upaya untuk memetakan ataupun membandingkan praktek manajemen yang pernah dipakai dengan state of the art yang ada sekarang. Condong untuk mengkotak-kotakan strategi dengan desain organisasi dan praktek manajemen perusahaan yang sudah-sudah.
Melihat strategi sebagai sebuah rangkaian Best Practices yang umum dilakukan perusahaan. Melihat state of the art teori organisasi pada masa lalu sebagai sebuah bukti konkret strategi yang mesti dilakukan. Padahal teori dan desain organisasi berkembang seiring waktu. Terobosan dan paradigma baru dalam ruang lingkup manajemen telah muncul dalam beberapa dekade terakhir.
Akibatnya, beberapa bagian buku ini lebih terasa seperti sebuah artifak kuno peninggalan praktek manajemen masa lampau. Utamanya, pandangan ketinggalan jaman yang mengatakan, secara implisit, bahwa organisasi seakan-akan seperti sebuah mesin yang tinggal disetir. Sebuah Pandangan yang masih terasa di setiap argumen buku ini.
Change Management untuk melakukan implementasi strategi yang sudah dipaparkan berikut kegiatan manajemen sehari-hari pun dilihat sebagai masalah arahan saja. Menghidupkan kembali mitos top management yang mendikte dan tahu segalanya, di mana bawahan tinggal mengikuti arahan dari atas. Kekurangan performa perusahaan lebih disebabkan karena kesalahan bawahan dalam mengikuti instruksi.
Sebuah pandangan yang secara perlahan mulai ditantang dalam satu-dua dekade terakhir. Ditantang, di antaranya, oleh karya-karya dari Edwards Deming, Peter Senge, Ikujiro Nonaka, dan H. Thomas Johnson. Karya-karya yang mengadvokasi pentingnya pembaharuan paradigma dan praktek manajemen saat ini.
Classical Strategy dalam buku ini mereka identikan dengan Command and Control style strategic planning, sebuah style manajemen yang lumrah dipraktekan banyak perusahaan sejak awal abad 20 lalu.
Classical strategy, mereka sebut, ditandai dengan dengan superior scale, superior capabilities, dan differentiation. Mempunyai karakter terpisahnya planning dan execution, learning dan doing.
Dia berdalih melalui computer simulation bahwa Strategy Classical ini cocok dipakai untuk market yang predictable, dan menghasilkan keuntungan lebih besar dibandingkan strategy lain (misal adaptive).
Masalahnya, Classical strategy untuk mencapai scale, differentiation, dan superior capabilities tidak harus dicapai dengan paradigma manajemen lama seperti command and control, tapi bisa juga dilakukan dengan cara mengaplikasikan teori manajemen baru.
Mengambil contoh Toyota, learning dan doing di Toyota dilakukan secara bersamaan, dan hanya bila dilakukan secara bersamaan lah pembelajaran yg sebenarnya bisa dilakukan. Dalam paradigma terbaru, learning dan doing tidak bisa dan tidak boleh dipisah. Padahal strategi Toyota masih sama seperti Classical Strategy. Bedanya, Toyota melakukan terobosan di praktek manajerial dan desain organisasi.
Contoh lain lagi adalah Royal Dutch/Shell. Berbeda dengan klaim mereka, Shell, walaupun bisa dikategorikan ke dalam Classical Strategy, juga telah melakukan berbagai terobosan manajemen dan desain struktur organisasi.
Semenjak tahun 1980an mereka mulai perlahan-lahan mengakui bahwa organisasi sejatinya adalah sebuah living being, sebuah living work community. Sebuah pandangan yang dikontraskan dengan mechanistic worldview yang lumrah dipraktekan berbagai organisasi. Dan sebagai akibatnya, praktek manajemen dan desain organisasi mereka harus ikut berubah.
Command and Control strategic planning gaya lama pun ditinggalkan. wewenang pun semakin didelegasikan ke bawah. Planning dan Learning dan Doing, mereka sadar, sebetulnya adalah satu hal yang sama.
Sebaliknya, Adaptive Strategy mereka kaitkan dengan experimentation secara terus-menerus oleh perusahaan. Sesuatu yang juga diadvokasikan oleh gerakan Lean Startup dan Agile product development. Lean/Agile pada pada dasarnya adalah sebuah framework yg dibuat agar perusahaan memiliki dua buah kapabilitas yang sangat krusial: mengerti customer dengan lebih cepat dan lebih baik, agar perusahaan mempunyai product market fit yang lebih tepat dengan cost yang lebih rendah.
Pada intinya, ia bertujuan untuk mempercepat feedback cycle bagi perusahaan, dan framework itu, sebetulnya, bisa berguna di perusahaan dengan jenis strategi manapun.
(Anehnya juga, mereka enggan menulis nama tools-tools dan practices terbaru seperti agile, lean, kanban, dsb, dan malah menggantinya dengan istilah-istilah umum seperti “perusahaan harus mempunyai portofolio eksperimen.” I wonder why?)
Selanjutnya, keberhasilan sebuah perusahaan pun seakan-akan dijadikan sebagai ultimate proof keberhasilan masing-masing jenis strategi tersebut. Padahal kita tahu bahwa keberhasilan sebuah perusahaan adalah sebuah hubungan sebab akibat yang kompleks, non-linear, dan multi-variable. Dengan banyak faktor yang berada di luar kontrol kita.
Detail dan teknik implementasi dari tiap-tiap strategi pun dijelaskan secara sambil lalu saja. Hanya membahas hal-hal super obvious dan umum. Quote “inspiring” dari business leader terkemuka pun ditambahi sebagai pemanis di akhir paragraf dari setiap poin-poin utama yang dimaksud.
Sebetulnya beberapa kritik saya ini juga dibenarkan oleh authornya sendiri, seperti pada halaman 21 dan 190. Pada kenyataannya, ujar mereka, perusahaan tidak bener-bener sekaku itu, tapi terdiri dari berbagai nuansa strategi dan implementasi yang saling bercampur. Dan framework ini berikut contohnya hanya melihat extreme endsnya saja.
Framework ini, sanggah mereka, baru akan mulai berguna ketika digunakan sebagai rule of thumb ketika menentukan arah perusahaan ke depannya. Sebuah tools diskusi ketika kita hendak memetakan perusahaan kita dengan lebih baik sehingga kita tidak sembrono dan terkungkung strategi yang itu-itu aja. Sebuah frame of mind yang berguna bagi kita agar kita bisa memulai “asking the right questions.”
Dan untuk itu saya setuju.